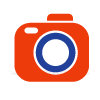Pandemi, Virus Corona, Bill Gates, Vaksinasi, WHO, Microchip, Elite, Kontrol Global. Apa yang ada pada benak kita saat menyimak kata-kata tersebut? Meskipun tidak tampak langsung terkait, namun kata-kata tersebut nyatanya sangat penting bagi banyak orang yang percaya teori konspirasi.
Lonjakan kepercayaan terhadap teori konspirasi berpadu dengan banyak hal teknis lainnya seolah sukses menumpulkan upaya untuk melawan penyebaran COVID-19. Saat tulisan ini dibuat, lebih dari empat juta dua ratus ribu orang telah meninggal karena COVID-19, lebih dari sembilan puluh delapan ribu dari Indonesia. Banyak ahli menyatakan angka tersebut terlampau besar, jika saja ada upaya lebih untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pakar medis dan juga pemerintah.
Faktanya, perdebatan terus saja berlangsung; penolakan terhadap kebijakan terkait penanganan pandemi juga tidak pernah redup, termasuk gerakan vaksinasi.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target dua juta vaksin per hari mulai Agustus 2021. Sampai 2 Agustus, Indonesia baru melakukan sekitar 20% target vaksin pertama dan hanya 95 target vaksin kedua. Angka yang tidak bisa dikatakan bagus.
Psikologi Konspirasi
Secara umum, teori konspirasi merupakan gagasan tentang kelompok orang kuat yang melakukan tindakan rahasia, rapi dan tersembunyi dari pengawasan publik. Ini secara inheren berarti bahwa mereka akan sangat sulit untuk disangkal. Bahkan bisa jadi seseorang yang percaya teori ini akan percaya bahwa siapa pun yang mencoba untuk menyanggah teori mereka sebenarnya menjadi bagian dari konspirasi itu sendiri.
Tapi bagaimana mungkin orang bisa percaya pada sesuatu tanpa bukti objektif? Adalah sah saja bila seseorang merasa skeptis terhadap peristiwa tertentu, tetapi adalah hal lain jika mereka menggunakan bukti serampangan untuk mendukungnya. Itulah yang dilakukan oleh para pemuja teori konspirasi, mereka bukan saja skeptis namun juga secara tidak sengaja ataupun sengaja menyebarkan informasi yang ujungnya akan menyebabkan misinformasi dan disinformasi serius, karena dirancang untuk merusak institusi sosial.
Sejak Februari 2020, WHO telah mengidentifikasi hal tersebut sebagai infodemik, sebuah badai informasi keliru yang menyebar berkaitan dengan pandemi. Melihat elemen-elemen kunci dari teori konspirasi akan membantu kita menjelaskan mengapa era media sosial, peningkatan konsumsi berita, dan kebingungan yang menyertai virus baru menciptakan lingkungan yang sempurna bagi munculnya konspirasi.
Jan-Willem van Prooijen, ahli psikologi Universitas Vrije Belanda memecah teori konspirasi menjadi lima bagian utama: (1) terdapat asumsi tentang bagaimana orang dan peristiwa saling berhubungan secara kausal atau membentuk beberapa pola; (2) sekelompok orang dengan sengaja merencanakan tindakan disebut konspirator; (3) para konspirator memiliki satu tujuan; (4) konspirator memberikan ancaman bahaya bagi banyak orang; (5) konspirator bekerja secara rahasia, itulah mengapa akan sulit mencari bukti tindakan mereka, namun sekaligus tidak bisa disangkal.
Kelima ciri tersebut akan lengkap jika kita mengetahui apa motivasi di balik seseorang percaya teori konspirasi. Karen Douglas, profesor psikologi dari Universitas Kent Inggris bersama dua koleganya dalam artikel jurnal yang berjudul The Psychology of Conspiracy Theories menyebut tiga alasan psikologis yang membuat seseorang tertarik untuk percaya teori konspirasi.
Mengapa aktivitas kita dibatasi? Mengapa dan sampai kapan sekolah dan fasilitas sosial tutup? Keganjilan demi keganjilan lainnya terus saja muncul dalam setiap benak seseorang saat pandemi. Satu mengapa belum selesai terjawab, muncul mengapa lainnya. Manusia membutuhkan pemahaman atas apa yang dilihat dan dirasakan.
Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka mungkin akan sangat menarik bagi bayak orang untuk percaya bahwa ada kekuatan yang berkomplot mengatur segala kekacauan. Inilah alasan pertama mengapa seseorang percaya teori konspirasi, bahwa manusia membutuhkan pemahaman tentang dunia secara pasti dan konsisten. Para ahli menyebutnya sebagai alasan epistemik (epistemic reason).
Badai informasi tentang penularan virus membuat manusia terus menerus merasa terancam dan tidak aman. Ketika manusia merasa terancam dalam beberapa cara, mendeteksi sumber bahaya dapat menjadi cara untuk mengatasi kecemasan. Teori konspirasi menawarkan jalan pintas untuk mendeteksi sumber bahaya, yaitu persekongkolan sekelompok orang kuat. Kita tidak akan mampu melihatnya dan membuktikannya, karena mereka adalah orang-orang kuat yang memiliki akses untuk bertindak dalam kerahasiaan. Inilah alasan eksistensial (existentital reason), alasan kedua mengapa seseorang mempercayai teori konspirasi.
Alasan ketiga mengapa seseorang termotivasi untuk percaya pada konspirasi karena alasan sosial (social reason). Para ahli psikologi berhipotesis bahwa dengan mempercayai konspirasi, seseorang merasa lebih baik tentang diri mereka dan kelompok sosial mereka sendiri karena ada kelompok lain sedang menginginkan sesuatu yang buruk. Ada semacam perasaan bahwa mereka sedang berperan sebagai pahlawan dalam cerita, karena mereka sedang berjuang melawan musuh besar yang tidak terlihat. Di sisi lain, plot rahasia dalam konspirasi membuat orang merasa istimewa, mereka merasa lebih tahu tentang apa yang terjadi di dunia. Merasa paling spesial.
Konspirasi dan Pengasuhan
Mengapa sebagian orang merasa cemas berlebihan saat berhadapan dengan masalah, sedang sebagian lagi terlihat berani menghadapinya? Terkait pandemi dan vaksin, kita sering menemukan kecemasan berlebihan, merasa tidak berdaya, terisolasi, dan frustrasi. Secara psikologis, kapasitas kita saat berhadapan dengan masalah sangat ditentukan oleh gaya keterikatan (attachment) dan pengasuhan yang kita dapatkan di awal-awal kehidupan.
Intinya, psikologi percaya bahwa pengalaman manusia dengan pengasuhnya di masa awal kehidupan mempengaruhi perkembangan dan perilaku di kemudian hari. Terdapat jenis ikatan yang diurai oleh Mary Ainsworth, yaitu jenis aman, menghindar, tidak terorganisir, dan jenis ambivalen.
Ketika pengasuh utama secara konsisten responsif terhadap kebutuhan bayi, menyampaikan dengan jujur, mencocokkan emosi dan kata-kata, anak cenderung mengembangkan keterikatan yang aman. Akibatnya, saat dewasa mereka akan percaya diri, mengembangkan kapasitas kognitif dan emosional secara seimbang, mampu menghadapi masalah dengan baik dan mampu menjalin kerjasama dengan baik. Anak yang diasuh dalam situasi penolakan akan mengembangkan keterikatan menghindar.
Saat dewasa, mereka akan terhambat secara emosional, tidak mampu memahami emosi dirinya sendiri, menyangkal kebutuhannya sendiri dan cenderung lepas dari situasi sosial, meremehkan orang lain dan pentingnya hubungan secara umum. Keterikatan tidak terorganisir dikembangkan oleh anak-anak yang diasuh dengan cara tidak konsisten –terkadang sayang dan perhatian dan terkadang tidak.
Anak-anak jenis ini tidak pernah merasa aman bahwa hubungan mereka stabil. Sehingga saat dewasa mereka belajar menggunakan emosi untuk memaksa orang lain dan bahkan untuk membela diri. Kapasitas logis mereka kurang berkembang. Mereka umumnya dalam keadaan waspada terus menerus. Sementara anak-anak ambivalen adalah anak-anak yang dibesarkan dalam situasi kekerasan dan pelecehan. Jika tidak diperbaiki, ini akan menjadi masalah gangguan psikologis di masa dewasa.
Studi terbaru menunjukkan bahwa orang dewasa dengan keterikatan tidak terorganisir lebih cenderung percaya pada teori konspirasi daripada jenis yang lain. Seseorang yang dibesarkan secara tidak konsisten sibuk dengan perasaan keamanan mereka, cenderung memiliki pandangan negatif terhadap kelompok luar, lebih sensitif terhadap ancaman, dan cenderung membesar-besarkan keseriusan ancaman tersebut. Parahnya, mereka tidak berorientasi pada argumen logis atau pernyataan faktual.
Jangan-jangan, apa yang terjadi sekarang memang merupakan imbas generasi. Banyak di antara kita yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan yang tidak konsisten. Artinya, kita tidak perlu terkejut dengan meningkatnya jumlah orang yang mempercayai cerita palsu, termasuk teori konspirasi yang dapat mengarah pada radikalisasi.
Apalagi jika dipadukan dengan algoritma media sosial yang menjebak kita pada arus informasi yang itu-itu saja mengikuti jejak informasi yang paling sering kita konsumsi sebelumnya. Pada titik ini, infodemik sepertinya akan terus berjalan. Sudah waktunya kita mengubah kebijakan dan institusi untuk mendukung kesejahteraan anak.