Surur, Misbahus (2013) Turonggo Yakso: berjuang untuk sebuah eksistensi. Syafni Press, Yogyakarta. ISBN 978-979-18012-3-2 UNSPECIFIED : UNSPECIFIED.
|
Text
13172.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Secara geografis, alam Trenggalek dibentuk dari dua lingkup ekologis, yang masing-masing memunculkan dua kebudayaannya yang unik. Selain disandingi oleh lautan, Trenggalek merupakan daerah yang dilingkupi pegunungan dan perbukitan. Kedekatan masyarakat terhadap dua ekologi ini yang telah terbina sejak lama, masing-masing memunculkan ciri khas kebudayaan, tepatnya keseniannya yang berlainan.
Dari lautan misalnya, Trenggalek punya tradisi upacara Longkangan di pantai Sumbreng (Kecamatan Munjungan) juga tradisi Larung Sembonyo di pantai Prigi (Kecamatan Watulimo) yang masih dilestarikan hingga kini. Sementara dari dunia pertanian, setidaknya tercipta kesenian jaranan yang khas Trenggalek. Kesenian ini lahir dari lingkungan pertanian di daerah Kecamatan Dongko. Sebuah kecamatan dengan komposisi wilayahnya yang sebagian besar pegunungan-perbukitan.
Seni jaranan khas daerah ini adalah Turonggo Yakso (perpaduan kuda-buto). Turonggo Yakso adalah kesenian yang banyak menyedot inspirasi dari upacara pertanian dalam rangka ”syukur(an)”. Upacara itu dinamai Baritan yang merupakan kepanjangan dari ”bar ngarit tanduran” (setelah musim panen saatnya menanam kembali). Dari upacara tersebut, singkat cerita, diciptakan sebuah tari dalam bentuk jaranan dengan gerak tari-tariannya yang unik.
Senarai gerak tari dalam Turonggo Yakso ini patronnya dikreasi dari intepretasi si pencipta tariannya dari tata cara masyarakat petani mengolah sawah. Mulai dari ketika petani datang ke sawah (mengolah sawah) hingga tiba saat musim panen. Karena itu, meski kesenian ini mengambil bentuk jaranan, substansi dan gerak tarinya berbeda dengan kesenian jaranan secara umum di Jawa Timur dan mungkin juga di Jawa Tengah. Tari ini diciptakan oleh seorang seniman Dongko, bernama Pamrih, dengan patron yang terbagi ke dalam ukel (gerak dasar) serta lawung (gerak kembangan atau tambahan).
Kesenian jaranan memang cukup lama dikenal di Jawa, khususnya di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seni jaranan sesungguhnya punya runtutan historis yang cukup panjang sejak kebudayaan masa Hindu-Budha di Jawa. Kala itu, ketika diadakan perayaan-perayaan peringatan hari-hari besar agama, atau dalam rangka menyambut kedatangan seorang raja, atau barangkali juga pembukaan sīma-sīma (semacam desa-desa) baru, selain dengan tradisi makan bersama, kerap pula diselingi dengan ”kesenian” yang dulu berupa pertunjukan-pertunjukan rakyat. Barangkali saja model kesenian ini, salah satunya, yang menjadi cikal atau embrio model kesenian macam jaranan itu di era yang jauh ke belakang.
Dan kalau kita amati, kesenian tradisi ini juga memanifestasikan kisah Pañji. Pañji, selain cerita kegemaran masyarakat kuno saat itu, kalau kita runut ke masa lampau, salah satunya, juga merupakan simbolisasi atau prototype dari sosok Airlangga, seorang raja besar masa Kahuripan (Jawa Timur). Sebagaimana kata Claire Holt dalam Art in Indonesia: Continuities and Change, kisah Pañji dalam banyak hal adalah gambaran bagi Arjuna Jawa Timur. Seorang pangeran mulia yang ideal dan tak terkalahkan dalam setiap pertempuran.
Tokoh atau konsep Pañji itu dalam seni jaranan diadaptasi ke dalam sosok penunggang kuda (ksatria). Di situ, seorang ksatria diharapkan mampu mengendalikan nafsu yang berada dalam diri buto (raksasa). Mengendalikan nafsu yang jelek tersebut agar dapat bekerjasama dengan para petani. Jadi kemampuan para ksatria dalam menunggangi kuda-buto (turangga-yaksa: kadang juga ditulis turonggo-yakso) tersebut digambarkan sebagai kemampuan untuk mengendalikan nafsu, bahkan menaklukkannya. Buto sendiri sering diartikan sebagai sebuah tenaga potensial. Dan njaran alias menunggangi kuda kepang (dari kulit sapi berkepala raksasa) sungguhnya adalah cara meluluhkan dan mengarahkan tenaga potensial yang berada dalam diri buto pada ranah kebaikan.
Adapun sedikit dari gerak dalam tari Turonggo Yakso di antaranya sebagai berikut: gerakan awal adalah sembahan yang menandai makna nenuwun (meminta; berdoa), digambarkan mirip gerakan mencabuti rumput yang mengganggu tanaman. Lalu terdapat ukel negar sengkrak yang merupakan gambaran bagi para petani sewaktu berjalan di pematang sehabis mencabuti rumput. Sedang saat petani mulai mengolah (mencangkul) tanah, digambarkan dengan ukel sengkrak gejuk. Ketika menanam (tandur) tergambar dalam ukel sirik gejuk. Sirik gejuk ini gerakannya jalan ke samping maupun ke belakang (nyirik). Dalam nyirik, biasanya kaki diangkat dan digejukkan (dihentakkan), karenanya dinamai sirik gejuk.
Lalu ada ukel gagak lincak, semacam membersihkan rumput dengan tangan kanan dan kiri, kemudian rumput dimasukkan ke dalam lumpur dengan cara diinjak dengan kaki. Pada saat petani memupuk tanaman ditandai ukel lompat gantung. Sementara saat tiba waktu panen digambarkan ke dalam ukel loncat gejuk. Loncat gejuk ini penggambaran aktivitas panen semacam nggeblok (memisahkan bulir padi dari tangkai) di sawah.
Itulah sedikit cuplikan dari beberapa landasan filosofi gerak dalam tari jaranan Turonggo Yakso, Trenggalek. Jalan cerita dan kekuatan tari jaranan ini tentu saja membedakannya dengan seni jaranan dari tempat lain. Jika digelar pada sebuah panggung lengkap dengan seperangkat gamelan, rias dan alur tari yang lebih komplit, akan tergambar bagaimana eksotika dunia persawahan (agraris) itu telah dipindah(-terjemah)kan ke dalam alur gerak tari jaranan yang tidak kalah eksotis dan menawan.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Keywords: | Turonggo Yakso; seni jaranan; seni tradisi; budaya Panji |
| Subjects: | 21 HISTORY AND ARCHAEOLOGY > 2102 Curatorial and Related Studies > 210202 Heritage and Cultural Conservation |
| Divisions: | Faculty of Humanities > Department of Arabic Language and Letters |
| Depositing User: | Misbahus Surur |
| Date Deposited: | 12 Apr 2023 08:44 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
 |
View Item |
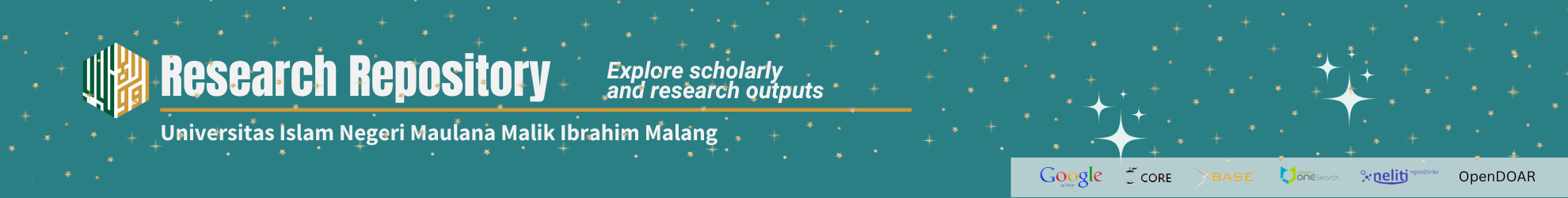
 Altmetric
Altmetric Altmetric
Altmetric